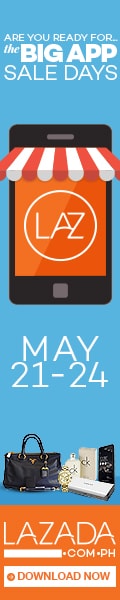Perhelatan Pilkada Buton Utara tahun 2020 sudah di depan mata. Riaknya sudah lama terasa terutama dalam perbincangan di media sosial. Tak hanya itu, wacana Pilkada juga telah mengisi diskusi-diskusi formal komunitas Pemuda dan juga perbincangan ringan semua kalangan masyarakat di waktu-waktu senggangnya.
Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, memilih pemimpin dalam sebuah pemilihan umum untuk periode waktu tertentu (Indonesia setiap lima tahun) adalah sebuah keharusan. Ini bertujuan untuk melakukan penyegaran (refresh) kekuasaan, karena kekuasaan yang terlalu lama bercokol dikhawatirkan akan ditumbuhi “lumut” dan “jamur” yang sulit diatasi.
Tapi Pemilu di setiap rumpunnya (Pilpres, Pileg, Pigub, dan Pilbup) tidaklah sesederhana itu. Penyegaran kekuasaan rupanya memiliki banyak implikasi. Salah satunya adalah implikasi pada karir pada ranah birokrasi. Hal ini terutama dialami para birokrat dalam perhelatan Pilkada.
Terkait dengan institusi birokrasi, Martin Shefter dalam buku “Political Parties and the State: The American Historical Experience” menerangkan dengan jelas bahwa dalam lingkungan yang memiliki otonomi birokrasi yang mapan sebelum politik demokrasi dijalankan, prosedur resmi (fomal) birokrasi bisa mencegah para politisi melakukan campur tangan dalam hal bagaimana para birokrat mengimplementasikan kebijakan negara.
Sebaliknya jika politik demokrasi dijalankan sebelum institusi birokrasi menjadi mapan dan otonom para pejabat terpilih biasanya dapat mengontrol birokrasi dan mengarahkan sumberdaya negara kepada tujuan-tujuan yang mengakomodir kepentingan mereka. Untuk mempermudah penguasaan itu, politisi terpilih bahkan menentukan para pejabat yang menduduki jabatan dalam birokrasi.
Dalam lingkungan seperti itu, utamanya pada ranah lokal, proses Pilkada juga dapat menjadi arena bagi ASN yang telah mencapai golongan tertentu untuk mengupayakan posisinya pada jabatan-jabatan strategis dalam birokrasi. Caranya adalah dengan mendukung politisi kuat yang menjadi kandidat dalam Pilkada.
Mengapa ini harus ditempuh oleh ASN? Karena dalam konteks lokal, tidak peduli sebarapa bagus karir seorang ASN, seberapa banyak sertifikat pelatihannya, jika kandidat yang didukungnya kalah, ia tidak akan mudah untuk memperoleh jabatan strategis dalam birokrasi. Sederhananya, sertifikat profesi akan dikalahkan dengan mudah oleh sertifikat sebagai tim sukses atau oleh kedekatan personal atau sebagai pendukung yang telah bekerja keras mencari suara untuk calon tertentu.
Kondisisi seperti ini melahirkan pola-pola hubungan spesifik yang disebut klientelisme politik. Aspinall dan Berenschot (2019) mendefinisikan klientelisme sebagai praktik pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat (uang, barang, pekerjaan, atau jabatan, layanan publik, kontrak-kontrak dengan institusi pemerintah, dsb.) dengan dukungan politik (suara, sumbangan dana kampanye, dukungan kampanye, dsb).
Dari definisi itu dapat dilihat bahwa klientelisme adalah praktek politik yang di dalamnya ada unsur pertukaran sumber daya negara termasuk jabatan yang bisa disediakan oleh para politisi dengan dukungan politik kepada para politisi itu. Dalam tulisan ini saya secara khusus menyoroti pertukaran jabatan birokrasi bagi ASN dengan dukungan politik selama Pilkada.
ASN, Konteks Formal dan Praksis
Secara formal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f dijelaskan bahwa penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada Asas Netralitas. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Penegasan asas netralitas ini sudah cukup jelas bahwa ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan para politisi. Oleh sebab itu pada Pemilu 2019 yang baru saja berlangsung larangan bagi ASN untuk terlibat politik seperti menjadi tim sukses, mengarahkan untuk mendukung calon tertentu, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, dan sebagainya ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Namun konteks formal bukan berarti tidak bisa dilanggar dan dilampaui. Selama Pemilihan Gubernur tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, kecenderungan kasus terbanyak yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara adalah masalah netralitas Aparatur Sipil Negara. Apalagi pada saat Pilkada mendatang, diperkirakan akan semakin banyak kasus pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh ASN.
Hal ini karena institusi birokrasi belum sepenuhnya otonom dan masih dapat dikendalikan oleh tangan para politisi yang berkuasa. Dengan demikian, untuk memacu karirnya di birokrasi, ASN mau tidak mau harus terlibat untuk mendukung (tidak hanya memilih) politisi tertentu.
Dengan demikian, Pilkada dapat dilihat sebagai arena bagi para ASN dengan kualifikasi golongan tertentu untuk menegosiasikan perolehan jabatan-jabatan penting di birokrasi. ASN yang ingin mendapatkan promosi jabatan dapat melakukan pertukaran dalam bentuk dukungan politik pada calon tertentu.
Di sinilah dilema ASN terjadi. Institusi birokrasi yang seharusnya tidak tercemar oleh masalah politik, ASN yang secara formal harus netral dalam arti tidak memihak kepentingan manapun terpaksa harus mengabaikan konteks formal dan menempuh praktik politik informal, dengan cara mendukung politisi tertentu yang sedang bertarung dalam pemilihan.
Ini harus dilakukan jika ingin karirnya di birokrasi berjalan baik dan efisien. Cara lainnya untuk memperoleh karir yang baik dalam birokrasi adalah dengan menyerahkan loyalitas penuh kepada politisi yang sedang berkuasa.
Begitulah sistem yang bekerja terutama dalam ranah lokal. Boleh dikatakan bahwa profesi ASN di daerah terjebak dalam sistem itu dan hampir tidak ada pilihan lain. Hal-hal formal dapat dilampaui dan hanya menjadi formalitas belaka. Karakter institusi seperti ini menurut Daron Acemoglu & Richard Robinson bersifat ekstraktif.
Ekstraktif dalam arti pengaturan menyangkut penyelenggaraan negara ditarik keluar dari ranah formalnya dan diatur sepenuhnya oleh hubungan-hubungan informal di panggung belakang. Yang tampak di depan adalah formalitas saja, sedangkan pengaturan yang sesungguhnya tetap dalam kendali politisi yang sedang berkuasa.
Hal ini tidak akan terjadi jika seandainya institusi birokrasi telah otonom dan bersifat inklusif, dalam arti tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan politisi yang sedang berkuasa dan dijalankan berdasarkan prosedur formal. Dalam birokrasi yang otonom, promosi jabatan akan dikembalikan pada konteks formal, seperti kualifikasi keahlian, prestasi dan golongan yang telah dicapai oleh seorang ASN.
Dengan demikian, birokrasi benar-benar fokus dalam melakukan pelayanan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan daerah tanpa harus terbebani oleh persoalan politik.
Watak Politik Klientelisme Kita
Tentu saja di sini saya tidak ingin menggeneralisasi bahwa tujuan seorang ASN mendukung politisi tertentu semata-mata karena jabatan. Sekali lagi tidak seperti itu. Ada banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi, seperti faktor kekeluargaan, pertemanan, dan lain-lain.
Namun, hal itu bukan berarti kita harus mengabaikan fakta-fakta sebaliknya, bahwa ada mekanisme pertukaran antara jabatan dan dukungan politik yang ramai terjadi dalam Pilkada. Ini bukan soal person, melainkan sebuah model politik yang menurut hasil penelitian Aspinall & Berenschot (2019) umumnya banyak terjadi di Indonesia.
Ini sekaligus menjelaskan bahwa selama ini pertukaran dalam politik yang sering disoroti hanyalah pertukaran antara uang dan dukungan politik yang disebut money politic. Pemilih diberi sejumlah uang agar memilih calon tertentu.
Padahal money politic (politik uang) hanya salah satu dari banyak praktek politik klientelisme. Selama ini pertukaran jabatan dan dukungan politik abai dalam perhatian. Tidak hanya itu program, kontrak-kontrak proyek, pemberian sejumlah barang yang tujuannya untuk mendapatkan dukungan politik dan untuk membalas dukungan politik adalah sama-sama praktek politik klientelisme.
Di sini politik klientelisme perlu dibedakan dengan politik programatik. Politik klientelisme adalah praktik politik dimana para politisi hanya mengarahkan penyaluran barang dan manfaat dari sumberdaya negara hanya kepada orang-orang yang memberikan dukungan politik padanya. Sedangkan model politik programatik memberikan barang dan manfaat bukan hanya kepada orang yang telah mendukungnya, melainkan kepada mereka yang berhak memperolehnya.
Menurut Aspinall & Berenschot (2019) politik klientelisme di Indonesia memiliki watak khusus jika dibanding dengan politik klientelisme di negara-negara seperti India dan Argentina.
Di Argentina dan India, yang menyalurkan barang dan manfaat kepada konstituennya atau yang menjadi perantara politisi dan konstituennya (broker) dilakukan oleh orang-orang yang secara formal adalah anggota partai politik.
Tetapi di Indonesia pada umumnya, juga menurut saya tak terkecuali di Buton Utara, orang-orang yang menjadi broker politik adalah dari pemilih itu sendiri yang secara formal bukan anggota partai, dan bukan pula bagian dari tim sukses yang bersifat adhoc. Broker politik ini bersifat informal tidak terdaftar sebagai anggota partai maupun sebagai tim sukses.
ASN, terlepas dari motivasi dukungannya, tidak terkecuali menjadi juga broker politik informal dalam upaya memberikan dukungan pada politisi tertentu yang sedang berkompetisi. Dalam politik klientelisme, jika calon yang didukung terpilih, dukungan politik ini membentuk relasi tawar-menawar, ada balasan yang diharapkan dari dukungan politik.
Itulah ciri khas dari politik klientelisme, ada mekanisme pertukaran yang terjadi antara pemilih dan politisi yang sedang berkompetisi.
NURLIN MUHAMMAD